| (Foto: Ilustrasi) |
(Tulisan ini pernah dimuat di kolom opini Harian ANALISA, Medan, 2007)
Listrik
merupakan salah satu sumber energi fisika yang berhubungan dengan hajat
hidup orang banyak. Selain memiliki nilai ekonomis, listrik juga
berfungsi sosial. Jika dilihat dari proses penemuannya, listrik sebagai
energi lahir untuk memudahkan problem aktifitas manusia. Listrik juga
telah dianggap sebagai penggerak peradaban manusia. Sehingga sangat
membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi,
budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Jadi, ketika sektor ini mengalami
krisis, maka memiliki efek domino atas sektor lainnya.
Energi
listrik sebagai material bergerak bukan hanya bersifat ilmu
pengetahuan. Pengaruhnya yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan
membuat energi ini menjadi komponen yang masuk dalam kebijakan politik.
Artinya, posisi dan peran strategis ketenagalistrikan dianggap sebagai
energi nasional suatu negara. Dengan demikian, sebagai energi nasional
yang strategis, dalam penyelenggaraannya, juga harus hati-hati.
Akan
tetapi, pengelolaan terhadap energi nasional yang strategis ini belum
sepenuhnya terpenuhi. Kompleksitas yang ada dalam ketenagalistrikan
menjadikan sektor ini dianggap tidak strategis bagi pembangunan
nasional. Terlihat dari produktifitas Perusahaan Listrik Negara (PLN)
yang belum merata dalam pendistribusian atas kebutuhan energi listrik
untuk seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat awam tahu benar , yang
tanpa pemahaman yang ilmiah, bahwa masih banyak daerah yang tidak
teraliri energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari, pemakaian listrik
secara ilegal (pencurian arus), pencurian kabel, manipulasi materan
listrik, penunggakan pembayaran, serta tidak adanya kuota yang berbeda
dari kebutuhan yang berbeda.
Jadi
asumsi masyarakat terhadap PLN adalah kinerja yang buruk, koruptif, dan
manajemen yang tidak profesional. Dari pihak PLN sendiri, yang menjadi
alasan atas persoalan krisis energi listrik ini adalah alokasi anggaran
yang kurang untuk semua kebutuhan produksi dan distribusi listrik
sehingga solusi alternatifnya adalah perlunya pasokan dari perusahaan
swasta.
Alasan Krisis
Krisis
terjadi ketika terjadi ketimpangan (disparitas) antara kebutuhan dengan
alat pemuas kebutuhan. Semakin tingginya tingkat kebutuhan untuk
konsumsi listrik di satu sisi, dan ketersediaan energi listrik yang
terbatas, menjadi penyebab pokok dari krisis. Akan tetapi, perlu juga
diperhatikan siapa saja subjek dominan dari konsumen listrik. Naiknya
kebutuhan energi listrik bagi kelompok ekonomi menengah ke atas bisa
dikatakan menjadi penyebab krisis. Sementara, sektor Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) yang paling merasakan dampak atas krisis listrik.
Kebijakan pemadaman listrik oleh PLN yang memakan waktu 4 jam sebanyak 3
kali per hari secara bergilir sangat merugikan bagi kelompok ekonomi
UMKM yang seluruh aktifitas produksinya bergantung pada PLN.
Krisis
ini direspon dengan unjuk rasa bagi elemen mahasiswa, pekerja, miskin
kota, pemuda, dan lainya dengan isu dan tuntutan yang berbeda. Seperti
aksi yang dilakukan oleh massa-aksi Front Rakyat Sumatera Utara (Rabu,
18/07/07) yang menuntut agar pemerintah menasionalisasi perusahaan
swasta, seperti PT Inalum, yang juga pemasok energi listrik bagi PLN. (Analisa, 19/07/07) Namun,
bila unjuk rasa tersebut hanya berisi tuntutan untuk pemenuhan energi
listrik semata tanpa ada konsepsi nasional yang melihat adanya pengaruh
kebijakan neoliberal, maka seluruh aksi-aksi dan tuntutan tersebut hanya
akan mendorong percepatan program neoliberal di Indonesia. Hal ini
terlihat dari perjanjian dan kerjasama yang digalang oleh pihak
pemerintah untuk sektor ketenagalistrikan hanya mengharapkan peran pihak
swasta. Justru disini pemerintah menciptakan ketergantungan pada pihak
swasta tanpa upaya pemandirian bangsa sendiri.
Neoliberalisasi Kebijakan
Jadi,
problem ketenagalistrikan muncul kepermukaan sejak dikeluarkannya
kebijakan resmi pada bulan Agustus 1998. Namun, mendapat tentangan dari
masyarakat sehingga pembahasannya terhambat. Perjalanan perubahan
kebijakan ketenagalistrikan terjadi seiring perubahan rejim
otoriter-birokratik-rente (Orde Baru) ke rejim reformasi. Di masa Orde
Baru, terdapat UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang
dianggap populis. UU ini masih mengatur jaminan terhadap kepentingan
umum yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan:”Usaha
penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan
oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan.”
Namun,
kebijakan populis ini, melalui agenda neoliberal yang dimotori oleh
lembaga keuangan internasional, yakni Asian Development Bank (ADB),
mendesak pemerintah RI untuk menderegulasi UU No. 15 Tahun 1985 dan
membuat UU Ketenagalistrikan yang baru. Dan pemerintah RI membuat
keterikatan perjanjian dengan pihak ADB pada tanggal 23 Maret 1999.
(Annual Report PBHI/2004)
Alasan
pemerintah untuk mengikutkan peran swasta dalam penyediaan energi
listrik karena keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan energi
listrik untuk kepentingan umum telah diusahakan pemerintah melalui
pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1989 dan Keppres No. 37 Tahun 1992,
meskipun kedua kebijakan tersebut bertentangan dengan UU No. 15 Tahun
1985.
Selama
kurang lebih tiga tahun (dari 1999 hingga 2002) pemerintah memenuhi
janjinya untuk memberikan jaminan atas liberalisasi ketenagalistrikan
melalui UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Perubahan
kebijakan ini bukan hanya perubahan yang bersifat teknis-prosedural
dalam penyediaan tenaga listrik, tapi juga sarat dengan kepentingan
ideologis kapitalisme global. Tampak jelas dari penafsiran yang berbeda
konsepsi dari pemaknaan atas “kepentingan umum”. Dalam Pasal 32 Ayat (1)
UU No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud “kepentingan umum” disebutkan:”Yang
dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang dilakukan
oleh pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.”
Dengan
demikian, deregulasi kebijakan sektor ketenagalistrikan memang
diarahkan untuk kepentingan kapital. Sehingga, logika penyediaan tenaga
listrik diselenggarakan bagi yang memiliki kapital besar. Pada akhirnya,
yang menjadi korban atas kebijakan neoliberal tersebut adalah
masyarakat. Penegasan tersebut ada dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 20
Tahun 2002, yakni tidak mempertimbangkan daya beli atau kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan tingkat keekonomian harga jual tenaga listrik yang hendak dicapai adalah untuk menjamin keuntungan pelaku usaha.
UU
tersebut bersifat sektoral dan sepihak tanpa memperhatikan kepentingan
nasional, yakni untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan kelompok
ornop melakukan perlawanan terhadap kebijakan neoliberal dengan cara judicial review
(peninjauan kembali) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang
membuahkan hasil positif dengan dibatalkannya UU No. 20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan dan memberlakukan kembali UU No. 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan.
Pelanggaran HAM
Negara,
yang dalam hal ini adalah pemerintah, sudah seharusnya memajukan,
memenuhi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Ketidakmampuan pemerintah
dalam hal penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan
pelanggaran HAM. Demikian juga dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak
sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Disini pemerintah telah melakukan
kekerasan terhadap warga negara melalui judicial violence (kekerasan melalui kebijakan). Namun, penyebab dari judicial violence ini adalah capital violence (kekerasan kapital) yang berasal dari hutang luar negeri dan penanaman modal asing.
Dari
situasi krisis tenaga listrik saat ini, pemerintah sepertinya akan
kembali menggunakan resep yang pernah dicoba sebelumnya, yakni dengan
membuat RUU Ketenagalistrikan yang baru.(Andalas,
20/07/07) Dengan melihat pikiran dan solusi dari pihak PLN dan
pemerintah sendiri, yakni dengan mengupayakan penyediaan tenaga listrik
dari pihak asing lewat perjanjian dan kerjasama, maka model kebijakan
yang diterapkan menjadi alat legitimasi program neoliberal.
Untuk
itu, sebagai perjuangan rakyat untuk mendapatkan hak atas pelayanan
publik yang layak dari pemerintah, maka seluruh elemen bangsa harus
bersikap kritis-konstruktif seluruh produk peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan semangat cita-cita proklamasi, Pancasila, dan
UUD 1945. Kemandirian bangsa terwujud dari kemampuan suatu bangsa untuk
berdikari di bidang ekonomi, berkedaulatan di bidang politik, dan
berkepribadian di bidang budaya.


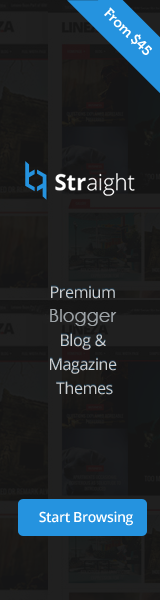











Tidak ada komentar
Posting Komentar