 |
| Ilustrasi |
Oleh : Pardo Gultom [1]
Perjalanan sistem politik di Indonesia memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin (23/07/07) mengeluarkan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang putusan perkara permohonan Pengajuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang pada dasarnya merupakan putusan untuk melegitimasi secara tegas posisi calon perseorangan dapat maju dalam sebuah pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati) tanpa partai politik. Putusan MK tersebut merupakan langkah maju dari pelembagaan demokratisasi baik secara nasional maupun lokal. Jadi, dengan demikian pelembagaan atas diskursus calon perseorangan tidak hanya terjadi di NAD saja, yakni melalui Pasal 67 Ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tetapi juga pada daerah lainnya.
Konsolidasi tersebut tidak hanya menyangkut keorganisasian, tetapi juga kepemimpinan dan penjaringan kader. Terlihat dari pasca keluarnya putusan MK tersebut, partai-partai juga mengeluarkan pendapatnya diseputar calon independen berupa dukungan terhadap mekanisme rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui sistem calon independen sebagai perkembangan dari demokratisasi. Selain itu, putusan MK ini juga menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi partai-partai yang tidak pernah dan yang belum efektif menjalankan fungsinya, seperti rekrutmen, pendidikan, dan sosialisasi. Mekanisme rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui calon independen, jika melihat kasus Pilkada Nanggro Aceh Darussalam (NAD), membuat partai-partai baik yang bersifat nasional maupun lokal, tidak mampu mengorganisir kemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah meskipun partai memiliki mesin politik hingga ketingkat desa-desa. Terbukti bahwa partai secara umum tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan basis massa
Perdebatan Konstitusional
Di dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tampak alur perdebatan dan sejarah kasus hingga putusan untuk mensahkan calon independen menjadi mekanisme baru dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Materi putusan yang berisi delapan puluh lima
Isi putusan MK ini secara garis besar merupakan putusan atas sengketa konstitusi dari seorang warga negara, yaitu Lalu Ranggawale (anggota DPRD Kab. Lombok Tengah) karena haknya untuk maju sebagai calon perseorangan dalam pilkada Kab. Lombok Tengah tidak dijamin dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketidaktegasan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menjamin hak perseorangan untuk dapat maju sebagai calon independen dalam pilkada. Secara konstitusional, terdapat pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan perseorangan untuk maju dalam pilkada, yakni Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) huruf a dan c, Ayat (6), dan Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2). Arti calon independen yang dimaksud adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya.
Sebagai jaminan konstitusional atas hak perseorangan untuk dapat dicalonkan sebagai calon independen, maka putusan MK tersebut membutuhkan perangkat hukum berupa revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya telah secara tegas mengatur hak-hak calon independen. Untuk itu, perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) melihat proses pembentukan dan revisi atas undang-undang memakan waktu yang lama. Sementara, kebutuhan terhadap aturan hukum yang mengatur ketentuan syarat calon independen mendesak dilakukan karena ada sekitar 14 daerah (propinsi) yang belum menyelenggarakan pilkada, antara lain Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulteng, NTT, Sumatera Utara, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali (Analisa, 10/08/07). Namun, belakangan pemerintah, yang dalam hal ini adalah presiden, justru berpendapat bahwa perangkat hukum yang tepat ialah melalui revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diharuskan untuk selesai paling lambat pada Januari 2008 (Analisa, 12/08/07).
Transformasi Politik
Perubahan politik lokal seperti apa yang bakal terjadi ketika jalur calon independen mulai berlaku? Apakah diskursus ini sepenuhnya memberdayakan potensi demokrasi lokal yang selama ini dianggap menjadi tiang penyangga terhadap demokrasi nasional kita? Atau malah sebaliknya, justru membangkitkan sentimen etnosentrisme dan primordialisme masyarakat lokal? Seperti halnya pilkada yang pernah berlangsung, tidak dapat dipungkiri bahwa sepenuhnya, baik calon maupun partai mempergunakan sentimen etnosentrisme dan primordialisme dalam menggalang dan memobilisasi kesadaran konstituennya.
Jika menimbang kekuatan antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkan oleh partai dengan calon independen, maka proses penarikan dukungan yang akan dipakai tidak akan jauh berbeda karena calon yang diusung partai maupun calon independen tetap mempergunakan sentimen-sentimen yang ada dalam masyarakat sendiri. Biasanya sentimen yang dipakai tidak jauh dari isu kultural (marga dan rumpun adat) yang menjadi basis kesadaran masyarakat yang mudah dimobilisasi, khususnya masyarakat pedesaan.
Anggapan bahwa calon independen akan lahir dari masyarakat sendiri dengan harapan ketika berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat langsung memperjuangkan kepentingan konstituennya merupakan harapan yang tidak jauh berbeda dengan harapan ketika masyarakat menentukan pilihan pada calon yang berasal dari partai.
Perbedaan yang kontras antara calon independen dengan calon dari partai politik adalah masalah pengorganisasian infrastruktur dengan suprastruktur politiknya. Calon independen tidak memiliki infrastruktur politik yang jelas. Sehingga, apa yang menjaga hubungan konstituen (infrastruktur) dengan lembaga eksekutif (suprastruktur) tidak ada. Justru posisi eksekutif yang diisi oleh calon independen tidak akan memperoleh legitimasi politik yang kuat dari DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota karena representasi dari kekuatan berbagai parpol.
Legitimasi Politik
Karena calon independen hanya mengandalkan kemampuan pribadi calon, maka yang si calon hanya dapat memperoleh legitimasi politiknya dari konstituen yang independen pula. Dalam timbangan pelembagaan demokrasi perwakilan melalui sistem pemilihan, maka calon independen dapat dianggap sebagai katup penyelamat antara massa
Selain itu, partai yang merasa mendapat “lawan tanding” baru, menganggap calon independen perlu mendapat ketentuan syarat pengajuannya. Dan ketentuan-ketentuan tersebut masih mengalami perdebatan. Ada
Tugas Calon
Prinsip demokrasi perwakilan adalah bahwa calon yang terpilih dapat mengagregasikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya bagi konstituennya saja. Jadi, jika calon yang berasal dari partai akan lebih mementingkan basis pemilihnya sendiri karena partai sudah memenangkannya, maka calon independen harus mementingkan masyarakat secara keseluruhan karena calon independen tidak hanya dikontrol oleh masyarakat, tetapi juga seluruh parpol. Dengan demikian, posisinya menjadi sorotan publik, baik dari kebijakan yang dihasilkan maupun aktifitas politiknya.
Selain itu, jika calon independent tidak memiliki basis massa pemilih yang kuat dan terorganisir, maka posisinya akan sama dengan calon yang diusung oleh partai yang hanya mengandalkan mobilisasi massa massa
* Tulisan ini pernah dimuat di Harian ANALISA, Medan, 2007.
[1] Penulis adalah Koordinator Jaringan Perjuangan HAM Sumatera Utara (JaPHAMSU). JaPHAMSU merupakan koalisi antarlembaga (ornop) maupun individu yang melakukan promosi, kampanye, dan advokasi kebijakan publik, dan advokasi HAM untuk penegakan Hak Asasi Manusia.
[1] Penulis adalah Koordinator Jaringan Perjuangan HAM Sumatera Utara (JaPHAMSU). JaPHAMSU merupakan koalisi antarlembaga (ornop) maupun individu yang melakukan promosi, kampanye, dan advokasi kebijakan publik, dan advokasi HAM untuk penegakan Hak Asasi Manusia.


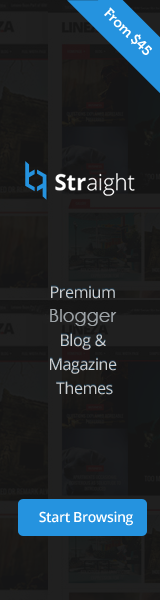










Tidak ada komentar
Posting Komentar