 |
| Buku Arief Budiman (Soe Hok Djin), Melawan Tanpa Kebencian. |
Oleh Siauw Tiong Djin
Persahabatan saya dengan Arief Budiman pernah diceritakan secara cukup panjang lebar oleh Arief sendiri dalam sebuah tulisannya yang berjudul Siauw Giok Tjhan yang Tidak Saya Kenal,terbit pada 1999 dalam buku yang saya sunting, Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan Baperki dalam sejarah Indonesia (Hasta Mitra, 1999).
Saya bergembira diberi kesempatan oleh, istri Arief, Leila Chairani Budiman, untuk secara umum dan terbuka menulis sesuatu tentang sosok pejuang dan sekaligus akademisi yang terkenal, Arief Budiman.
Nama Arief Budiman, yang juga dikenal sebagai Soe Hok Djien, tentunya sudah lama saya dengar sejak saya masih di SMA pada 1970-an. Saya-pun mengetahui nama adiknya yang juga ternama, Soe Hok Gie. Pada waktu itu saya ketahui bahwa mereka turut aktif mendukung Soeharto pada awal 1966 dan merupakan bagian dari kelompok yang memusuhi ayah saya, Siauw Giok Tjhan.
Perhatian dan kekaguman saya terhadap sosok Arief Budiman meningkat ketika saya membaca berbagai berita tentang keberanian Arief menentang kebijakan pemerintah "Orde Baru" yang turut ia dukung perwujudannya. Arief berada di garis depan keras menentang korupsi dan menentang proyek Tien Soeharto, pembangunan Taman Mini pada 1970-an. Oleh karenanya ia dan kawan-kawan sempat ditahan militer.
Pada 1972, di salah satu kesempatan bezoek untuk bertemu dengan ayah, saya bertanya tentang Arief Budiman. Ayah menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Arief dan Hok Gie, tetapi ia kenal baik dengan ayah mereka, Soe Li Piet. Ayah pada waktu itu meringkuk di penjara sebagai seorang tahanan politik. Ia merupakan salah seorang korban kejahatan negara yang dipimpin oleh Soeharto. Bersama ratusan ribu tahanan lainnya dipenjarakan tanpa proses peradilan apapun.
Ternyata Soe Li Piet, merupakan salah satu wartawan atau penulis yang bekerja di mingguan dan harian yang dipimpin oleh ayah di Jakarta, mingguan Sunday Courier, mingguan Suara Rakyat dan harian Republik.
Arief bercerita ke saya bahwa ia dan Hok Gie pada 1950-an, sering diajak ayahnya ke kantor percetakan Sunday Courier di jalan Pintu Besar, Kota. Mereka bermain di kantor percetakan sambil menunggu ayahnya menyelesaikan tulisan-tulisannya atau tugas-tugas lainnya.
Arief kecil pada waktu itu tidak mengetahui banyak tentang Sunday Courier dan siapa yang memimpinnya. Ia cukup terperanjat ketika pada 1988, di pertemuan pertama saya dengannya di Melbourne, saya ceritakan bahwa Sunday Courier dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan. Dan lebih terperanjat lagi ketika saya ceritakan bahwa ayahnya, Soe Lie Pit, mengenal baik Siauw Giok Tjhan, tokoh Tionghoa yang sempat ia "musuhi" di zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
Pada 1987, saya memutuskan untuk berkenalan dengan Arief dan menulis surat kepadanya yang berada di Salatiga. Arief tentu tidak mengenal saya. Dalam surat tersebut saya mengucapkan salam kenal dan memohon kesediaannya untuk berpartisipasi dalam upaya membela komunitas Tionghoa yang menurut saya selalu mengalami dampak negatif kebijakan rasisme pemerintah. Ia menjawab surat tersebut dengan nada cukup dingin: ...Mengapa harus dibela?...
Korespondensi tersebut tidak saya lanjuti. Saya beranggapan, mungkin Arief memang hanya ingin berjuang sebagai seorang "pribumi", karena merasa sudah ter"asimilasi" dalam tubuh Indonesia. Pada waktu itu, sebelum saya bertemu muka dengannya, saya ketahui bahwa ia merupakan seorang tokoh yang mendukung paham asimilasi. Paham ini menganjurkan Tionghoa menanggalkan ke-Tionghoa-annya untuk menjadi orang Indonesia yang baik. Jadi timbullah anjuran mengganti nama dari Tionghoa ke nama yang tidak Tionghoa; menghentikan tindakan ritual Tionghoa seperti sembahyang cara Konghucu atau Tao-isme; tidak merayakan tahun baru Imlek; dan menghilangkan ciri-ciri biologi Tionghoa generasi penerus melalui kawin campuran, kawin dengan orang-orang "asli" atau "pribumi".
Paham ini diformulasikan pada 1960-an oleh LPKB (lembaga Pembina kesatuan Bangsa), sebuah lembaga yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Tionghoa berhaluan politik "kanan", dengan dukungan militer dan berbagai partai politik Islam, Katolik dan Kristen.
Paham asimilasi ditentang keras oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan. Baperki memformulasikan paham integrasi, yang kini lebih dikenal sebagai multi-kulturalisme atau pluralisme. Siauw mendorong Tionghoa menerima Indonesia sebagai tanah airnya dan mengintegrasikan dirinya dalam berbagai kegiatan membangun Indonesia, tanpa menanggalkan ke-Tionghoa-an masing-masing. Baperki berpendapat bahwa ukuran patriot Indonesia tidak berkaitan dengan latar belakang ras dan agama seseorang. Baperki didukung oleh kekuatan politik "kiri" (PKI, PNI, Partindo dll) dan Presiden Soekarno.
Pertentangan antara Baperki dan LPKB dengan sendirinya meruncing di zaman Demokrasi Terpimpin, sehingga timbul kategori absurd. Integrasi dinyatakan jalan keluar "kiri", sedangkan asimilasi adalah jalan keluar "kanan".
Padahal kedua-duanya memiliki meritsbilamana dikembangkan secara wajar, tanpa paksaan.
Setelah Jendral Soeharto mengukuhkan kekuasaannya pada tahun 1966, Baperki dibubarkan. Banyak pimpinannya dibantai atau dimasukkan ke dalam penjara. Paham asimilasi berubah menjadi kebijakan pemerintah. Semua yang tadinya bersifat anjuran, dijadikan undang-undang. Terjadilah sebuah proses cultural genocide selama 32 tahun. Imlek dilarang untuk dirayakan. Pelaksanaan ritual Tionghoa di depan umum dilarang. Penggunaan bahasa Tionghoa dilarang. Walaupun pergantian nama tidak menjadi undang-undang, tetapi banyak Tionghoa dipaksa untuk mengganti namanya. Berbagai peraturan dan Undang-Undang rasis dikeluarkan dan dilaksanakan.
Pada zaman Demokrasi Terpimpin Arief termasuk tokoh yang mendukung aliran asimilasi. Dan memang ia bisa dikatakan masuk dalam aliran "kanan", karena bersikap anti Bung Karno dan anti "kiri".
Pada 1980-n saya sudah menetap di Australia dan sempat membaca berbagai tulisan Arief. Saya mendeteksi adanya perubahan haluan apalagi setelah ia kembali ke Indonesia dari Harvard University pada akhir 1970-an. Saya tidak lagi melihat garis "kanan". Dari Herb Feith, seorang Indonesianis yang ternama, saya kemudian ketahui, bahwa ketika Arief menyelesaikan program PhD nya di Harvard University pada akhir 1970-an, Arief "menjelma" menjadi seorang Marxist.
Itulah yang menyebabkan saya menulis surat kepadanya pada 1987. Dan jawaban dinginnya cukup mengecewakan saya.
Pada akhir 1988 Arief menetap di Melbourne selama 3 bulan. Di periode itu-lah saya berkenalan dan bersahabat dengannya. Sejak pertemuan pertama kami merasa cocok. Kami kerap bertemu selama tiga bulan tersebut. Dan pada masa itulah saya bertemu pula dengan isteri Arief yang cantik dan manis budi, Leila.
Saya sangat mendambakan pembicaraan/pertemuan dengan Arief dan Leila. Persahabatan Arief-Leila dan saya bersama isteri, Leony menjadi lebih erat ketika Arief sebagai professor di Universitas Melbourne, menetap di Melbourne sejak 1997.
Saya segera mendapati Arief memiliki sikap pejuang tetapi sekaligus akademisi. Ia pun menunjukkan kejujurannya. Attributes ini nampak sekali dari pembicaraan-pembicaraan dengannya dan seminar-seminar yang ia berikan. Ia dengan tegas menunjukkan bahwa ia menentang rezim Soeharto yang menurutnya lalim, mengkhianati rakyat Indonesia dan korup. Serangan atau kritikan tajam terhadap rezim ini didasari berbagai argumentasi akademik yang sulit untuk dibantah.
Ia meminta maaf atas tanggapannya yang dingin terhadap permintaan saya yang saya tuangkan dalam surat pada 1987. Ia menyatakan bahwa ia menganggap ajakan saya itu berupa dorongan untuk mendirikan sebuah organisasi yang membela kepentingan para pedagang Tionghoa kelas kakap yang berada di sekitar Soeharto. Ia menyatakan bahwa asumsi itu jelas salah.
Salah satu topik pembicaraan kami adalah pertikaian antara asimilasi dan integrasi. Pembicaraan berjam-jam ini sangat menggembirakan saya, karena ternyata Arief, seperti yang ia katakan dalam tulisan Siauw Giok Tjhan yang saya tidak kenal, dengan jujur menyatakan bahwa ia bersalah mendukung paham asimilasi di zaman Demokrasi Terpimpin. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia bukan saja menerima paham integrasi tetapi bertekad untuk mendorong semua yang ia bisa pengaruhi untuk mendukung paham ini.
"Janji" ini ditepatinya. Dalam berbagai ceramah, terutama setelah peristiwa Mei 1998, ia kerap mencanangkan betapa pentingnya Indonesia merangkul pluralisme atau multi-kulturalisme. Perbedaan itu, menurutnya adalah sesuatu yang indah.
Demokrasi Terpimpin di mana Soekarno menjadi pemimpin besar yang memiliki kekuasaan absolut, bagi Arief, merupakan pembunuhan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Oleh karenanya ia keras menentangnya. Inilah yang menyebabkannya mendukung pembentukan Orde Baru pada awal 1966. Tidak disangkanya bahwa rezim yang didukungnya ini malah melakukan penghancuran demokrasi dan penginjakan HAM luar biasa. Oleh karena itu, ia-pun keras menentangnya.
Yang menarik, rezim-rezim pengganti Soeharto pun tidak luput dari kritikan-kritikan tajamnya. Ia pernah mengkritik sikap Gusdur yang kurang profesional sebagai presiden. Dan ia menyindir Megawati bersikap seperti seorang ratu sehingga menimbulkan antipati di antara para pendukungnya.
Sebagai seorang pejuang, ia tidak segan mengecam tokoh-tokoh politik yang menurutnya korup dan tidak merakyat, walaupun mereka merupakan kawan-kawan pribadinya. Tetapi ia tidak pula segan dengan jujur memuji tokoh-tokoh yang memiliki sikap dan pandangan yang ia anggap baik untuk Indonesia, walaupun yang ia puji itu bertentangan pendapat dengannya.
Misi perjuangannya adalah membangun Indonesia yang pluralistik, adil dan demokratik. Di sinilah kita bisa menilai kualitas Arief sebagai seorang pejuang. Ia tetap konsisten dengan misi ini. Siapa-pun yang menghambat misi perjuangan ini akan ia labrak.
Yang unik, Arief bukan sekedar pejuang yang gagah berani berada di barisan depan gerakan mencapai perbaikan. Ia mahir menuangkan pikiran-pikiran membangun secara akademik. Dan pemikiran secara ilmiah yang mudah untuk diikuti inilah, dalam berbagai periode perjuangan mencapai sebuah perbaikan, lebih dibutuhkan ketimbang sekedar yel-yel dan seruan dalam berbagai acara demonstrasi.
Tetapi begitu ada kesempatan untuk berdemonstrasi di jalan, ia tidak segan turun ke lapangan. Saya ingat ketika pada waktu kami bersamaan berada di Jakarta pada bulan November 1998 dan berjanjian untuk kembali ke Melbourne bersama pada 13 November, di waktu mana terjadi Peristiwa Semanggi. Saya diberitahu teman ketika rapat untuk segera berangkat ke Bandara sebelum pukul 3 sore. Anjuran teman tersebut saya ikuti. Saya coba mencari Arief, untuk mengajaknya pulang berangkat barengan ke bandara. Tapi saya tidak berhasil menghubunginya. Setiba di Melbourne saya tahu bahwa Arief bukannya ke bandara tetapi memilih terjun berdemonstrasi di depan kampus Universitas Atmajaya.
Selama 10 tahun belakangan ini, karena faktor kesehatan, Arief "menghilang" dari dunia perdebatan politik ilmiah tentang Indonesia. Akan tetapi orang akan selalu ingat atas jasa-jasa Arief Budiman dari kehadirannya di Indonesia sebagai seorang pejuang yang sekaligus akademisi, dalam perjuangan mewujudkan Indonesia yang pluralistik, adil dan demokratik.
-----
SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL
oleh: Arief Budiman
Saya belum pernah bertemu dengan almarhum Siauw Giok Tjhan, bekas Ketua Baperki yang pernah di penjara oleh pemerintah Suharto. Saya tidak mengenalnya. Dia meninggal di Negeri Belanda setelah dia dilepaskan dari tahanannya beberapa tahun yang lalu.
Tapi tentu saja saya mengetahui apa yang dilakukan olehnya selama hidupnya.
Apalagi kemudian saya menjadi akrab dengan dua anggota keluarganya. Mula-mula saya berkenalan dengan putra dari adik Pak Siauw yang bermukim di Eropa. Namanya Siauw Tiong Gie. Orangnya berani melakukan petualangan dalam arti yang positip, sangat lincah dan informal. Kemudian saya juga bersahabat baik dengan putra Pak Siauw sendiri yang bermukim di Australia: Siauw Tiong Djin. Sifatnya tidak beda, penolong dan baik hati, cuma dia lebih sopan dan kurang ugal2an ketimbang Gie.
Dengan kedua orang Gie dan Djin ini, saya langsung merasa cocok dan akrab. Ini agak aneh, karena dengan Pak Siauw sendiri, secara politik saya “bermusuhan.”
Sebagaimana diketahui, dalam hubungannya dengan politik masalah orang-orang Indonesia keturunan Cina[1] (selanjutnya disebut orang Cina saja) di Indonesia, ada dua kubu yang saling berseberangan. Yang pertama adalah Kubu Integrasi yang dipelopori oleh Baperki. Yang kedua adalah Kubu Asimilasi yang dipelopori oleh LPKB atau Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.
Secara singkat Kubu Integrasi memperjoangkan keaneka-ragaman budaya atau “multi culturalism”. Doktrin Integrasi meminta supaya orang-orang Cina diakui sebagai salah satu suku, disamping suku-suku yang sudah ada di Indonesia. Ke-Cina-an dari orang ini tidak usah dipersoalkan, seperti juga kita tidak mempersoalkan ke-Jawa-an, ke-Batak-an atau ke-Minang-an dari suku-suku ini. Budaya Cina juga patut dikembangkan, seperti halnya kebudayaan Jawa, Batak atau Minang. Semua kebudayaan ini seharusnya dianggap sebagai kekayaan budaya Indonesia yang mendasarkan diri pada semboyan Bhineka-Tunggal-Ika: Ber-aneka-ragam Tapi Satu.
Kubu Integrasi bertentangan dengan Kubu Asimilasi. Bagi mereka orang-orang Cina di Indonesia tidak bisa disamakan sebagai salah satu suku, karena asal mereka bukan dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Mereka berasal dari daratan Cina. Kubu ini menguatirkan, kalau budaya dan identitas mereka dikembangkan, akan terjadi loyalitas ganda dalam sikap kebangsaan orang-orang Cina ini. Kepada yang mana mereka harus lebih setia, Cina atau Indonesia? Karena itu, kubu Asimilasi menginginkan supaya orang-orang Cina menghilangkan identitas budayanya dan melebur ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Perkawinan campur antara orang-orang Cina dan orang-orang pribumi dianjurkan (bukan dipaksakan seperti sering dituduhkan kepada kubu ini oleh lawan-lawan politiknya) oleh Kubu Asimilasi sebagai salah satu usaha peleburan total, badaniah dan rohaniah.
Ketika saya remaja dan menjadi mahasiswa, saya tertarik kepada Doktrin Asimilasi ini. Pada waktu itu saya melihat ada semacam sikap sombong pada banyak orang Cina yang saya kenal terhadap orang-orang pribumi. Mereka menganggap orang-orang pribumi sebagai ras yang lebih inferior. Orang-orang pribumi ini dipanggil sebagai “orang kampung,” dianggap malas dan kerjanya cuma makan saja.
Orang-orang pribumi ini sering dipanggil dengan istilah ejekan “fan kui” atau “setan nasi.” Pendeknya orang Cina menganggap orang pribumi sebagai lebih rendah. [2]
Pada saat itu saya sependapat dengan Doktrin Asimilasi bahwa solusinya adalah bila orang-orang Cina melakukan “asimiliasi’, yakni meleburkan diri ke dalam budaya orang-orang Indonesia dan menghapus ke-Cina-annya. Saya berpikir, sebagai pendatang yang tinggal di negeri ini, orang-orang Cina-lah yang sepantasnya menyesuaikan diri.
Keberpihakan saya pada Doktrin Asimilasi kemudian diperkuat karena saya kemudian bergaul dengan tokoh-tokoh dari orang-orang Cina yang mendukung doktrin ini, seperti Bapak P.K. Ojong, Pak Yap Thiam Hien, Pak Oei Tjin San, dan sebagainya.
Saya melihat mereka sebagai orang-orang jujur dan integritas kepribadiannya baik. Karena itulah saya juga mengidentifikasikan diri saya sebagai bagian dari kelompok Kubu Asimilasi. Apalagi kemudian adik saya, Soe Hok Gie, aktip di LPKB.
Pada saat itu, yakni permulaan tahun 1960an, sedang terjadi polarisasi politik. Disatu pihak terdapat kubu Bung Karno, yang didukung oleh kelompok politik kiri seperti PNI (terutama yang sayap kiri, yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dan Surachman) dan terutama PKI. Baperki juga masuk ke dalam kelompok ini. Di pihak lain ada kelompok politik kanan yang didukung oleh kelompok2 politik agama (Islam, Kristen, Katholik) dan juga militer, terutama Angkatan Darat. Kedua kelompok ini saling bersaing, dan saling menyusun kekuatan. Tampaknya kedua kelompok ini merasa pada suatu waktu mereka akan menghadapi sebuah pertempuran akhir yang menentukan. Karena itulah mereka ber-lomba-lomba mencari pendukung.
Tentu saja pada saat itu, Bung Karno masih sangat kuat, mengatasi kedua kelompok yang saling bersaing ini. Karena kedekatannya dengan Bung Karno, dan kecenderungan Bung Karno untuk berpihak kepada mereka, maka kelompok kiri juga menjadi lebih kuat, dan lebih agresip ketimbang kelompok kanan, meskipun yang terakhir ini didukung oleh militer. Pada saat itu, militer secara politis tunduk dan relatip lebih lemah dalam menghadapi Bung Karno.
Keadaan politik ini mempengaruhi juga kedua kelompok orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Karena Kubu Integrasi dibela oleh Baperki yang merupakan partai yang dekat dengan pusat kekuasaan, maka militer mendekati Kubu Asimilasi dan mendirikan LPKB untuk menampung aspirasi mereka.
Saya sendiri pada waktu itu lebih tertarik pada kegiatan kesenian (khususnya kesusastraan dan seni-lukis) ketimbang politik. Karena itu saya terlibat dalam kelompok Manikebu. [3] Segera saya dan adik saya Hok Gie terlibat dalam kancah perseteruan politik antara kelompok kiri dan kanan, meskipun kami terlibat dalam dua organisasi yang berbeda.
Tapi, kelompok Manikebu tidak bertahan lama. Pada tanggal 8 Mei 1964, Presiden Sukarno secara resmi melarang Manikebu. Segera setelah itu, orang-orang yang terlibat Manikebu menjadi bulan-bulanan demonstrasi an mereka yang bekerja di lembaga pemerintah digusur dari jabatannya, seperti misalnya Wiratmo Sukito dari Radio Republik Indonesia dan H.B. Jassin dari jabatannya sebagai Dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Para pengarang dan penulis yang tidak punya jabatan tidak boleh menulis di media, atau tepatnya media tidak berani memuat tulisan mereka untuk menghindari diri dari demonstrasi massa kelompok kiri. Atau kalaupun dimuat, harus dengan nama samaran.
LPKB lebih beruntung nasibnya. Mungkin karena militer secara langsung terlibat di dalamnya. Ketuanya adalah seorang perwira Angkatan Laut keturunan Cina, Sindhunata. Juga beberapa tokoh partai dan mahasiswa, termasuk mereka yang dari
kalangan Islam, seperti Hary Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Cosmas Batubara, Slamet Sukirnanto, Anis Ibrahim, terlibat secara organisatoris dengan lembaga ini. Dalam aspek ini, kubu Manikebu lebih lemah, karena hanya merupakan kelompok
seniman.
•••
Saya “mengenal” Siauw Giok Tjhan dalam perspektip politik ini, yakni sebagai Ketua Baperki yang ada di “seberang sana.” Kelompok “sana” dengan agresip menyerang kami, dengan selalu menekankan dirinya sebagai kelompok yang lebih “progresif revolusioner menentang kaum Neo-Kolonialisme-Imperialisme alias Nekolim, pendukung setia tanpa reserve Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI/Presiden Seumur Hidup Sukarno.” Sedangkan kami dianggap sebagai kelompok reaksioner dan kontra-revolusi antek Nekolim.[4] Hanya karena ada militer yang mendukung kami, maka Manikebu masih bisa hidup untuk sementara, dan LPKB masih terus bertahan.
Barangkali, bisa dipahami sekarang mengapa saya punya pandangan yang negatip terhadap Siauw Giok Tjhan yang suka mengganyang musuhnya yang lebih lemah.
Kelompok kiri yang bergabung dengan pusat kekuasaan pada waktu itu memang cukup agresip dan cukup kasar mengganyang kami. Dan Baperki yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan ada di sana.
Tapi, keadaan politik tiba-tiba berubah sejak bulan Oktober 1965. Militer berhasil menyingkirkan Bung Karno dan membantai kaum kiri, terutama mereka yang jadi anggota PKI. Tokoh-tokoh dan aktivis kiri dari partai lainnya banyak yang ditangkap dan dimasukkan penjara tanpa peradilan, termasuk Siauw Giok Tjhan.
Sebagai orang yang menjadi kurban dari penindasan Demokrasi Terpimpin-nya Sukarno, saya tentu saja menyambut perubahan ini. Saya berharap Indonesia akan memasuki era demokrasi. Beberapa teman sarjana dan wartawan asing memang mentertawakan kenaifan saya dan berkata:
“Bagaimana kamu bisa mengharapkan
demokrasi dengan cara bekerja-sama dengan militer?” Tapi saya tidak peduli, karena pada saat itu hanya militerlah kekuatan yang bisa membendung Sukarno.
“Saya tidak peduli neraka apa yang akan saya masuki nanti. Yang penting kita keluar dulu dari neraka ini.” Begitu kata saya kepada mereka.
Segera, saya melihat “neraka” apa yang saya masuki. Militer yang berkuasa segera melakukan pembunuhan masal terhadap orang-orang yang dituduh PKI, dan memasukkan mereka ke penjara. Mereka yang memprotes, meskipun dulu membantu militer melawan Bung Karno dan kekuatan kiri lainnya, juga diperlakukan dengan keras. Misalnya ketika H.J.C. Princen menceritakan pada Harian KAMI tentang kuburan masal yang dia temukan di Purwodadi. Pak Princen atau Poncke, begitu dia secara akrab dipanggil, segera diintimidasi. (Untunglah Poncke punya banyak teman di kalangan
militer, sehingga dia tidak sampai dicelakakan.) Militer makin melebarkan cengkeraman kekuasaannya, dan demokrasi jadi makin menjauh.
Dalam hal kebijakannya terhadap warga keturunan Cina, pemerintah militer dibawah Jendral Suharto melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Apa yang dulu merupakan polemik intelektual antara kubu Baperki dan LPKB tentang posisi warga keturunan Cina, sekarang posisi ini (yakni yang dianut oleh LPKB) dipaksakan dengan bantuan kekuasaan negara. Doktrin Integrasi bukan saja dilaksanakan, tapi dilaksanakan secara sangat ekstrim. Pertama, secara resmi istilah Tionghoa diganti menjadi Cina, sebuah istilah yang dianggap menghina bagi kelompok Cina waktu itu. Kemudian segala bentuk ekspresi budaya Cina dilarang: huruf Cina, perayaan tradisional Cina seperti Tahun Baru, pertunjukan barongsai dan naga, dan sebagainya. Bahkan nama orang dianjurkan diganti menjadi nama Indonesia. Cuma kawin paksa saja yang tidak dilakukan.
Pada waktu itu, menghadapi tindakan-tindakan pemerintah terhadap orang-orang Cina ini, saya merasa serba salah. Sebagai orang yang mengikuti Kubu Asimilasi dulu, yang menginginkan supaya orang Cina meleburkan diri menjadi orang
Indonesia, saya merasa ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru ini. Tentu saja saya tidak menyangka bahwa pemerintah Suharto melaksanakan Doktrin Asimilasi sampai sejauh itu. Doktrin ini, menurut saya, sudah dilaksanakan secara terlau ekstrim, misalnya sampai orang-orang Cina harus mengganti nama yang diberikan oleh orang tuanya.
Saya melakukan pembicaraan dengan adik saya, Soe Hok Gie, yang juga tidak setuju dengan tindakan sejauh itu, terutama soal ganti nama. Apalagi Pak Yap Thiam Hien secara tegas menolak mengganti namanya.
Tapi saya dan Hok Gie berpendapat, kalau orang seperti kami, yang sudah mulai dikenal sebagai tokoh oleh masyarakat waktu itu, tidak mengganti nama, maka kemungkinan akan ada banyak orang-orang Cina yang juga tidak akan mengganti namanya. Kalau nanti ada tindakan diskriminatif lebih jauh oleh pemerintah maupun oleh oknum-oknum di kalangan pemerintah, orang-orang biasa yang ada dibawah akan menjadi kurban. Bagi orang-orang seperti kami, kami bisa melawan karena kami punya hubungan yang erat dengan pers, serta punya “koneksi” dengan perwira-perwira tinggi militer. Atas dasar itu kami putuskan bahwa adalah tanggung jawab sosial dan politik kami untuk mengganti nama kami menjadi nama Indonesia.[5]
Selanjutnya, secara lambat laun, setelah menyaksikan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Suharto terhadap orang-orang keturunan Cina di Indonesia, ber-angsur-angsur saya melihat bahwa Doktrin Assimilasi merupakan sebuah doktrin yang salah. Salah satu yang menyadarkan saya adalah pengalaman saya ketika belajar di Amerika Serikat selama 8 tahu, yakni dari tahun 1973 sampai 1981.
Disana saya melihat bahwa orang-orang Hitam memperjoangkan identitas budayanya, tanpa mengurangi sikap nasionalis mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang Amerika. Dengan semboyan “Black is Beautiful,” mereka mempopulerkan kebudayaan Afro-Amerika, dan ini pada gilirannya memperkaya misalnya musik Amerika. Saya melihat bahwa kita bisa tetap mempertahankan kebudayaan etnis kita, tanpa menjadi kurang nasionalis. Nasionalisme dan etnisitas bukanlah dua hal yang saling meniadakan, tapi mereka bisa saling berinetraksi dan saling memperkaya. Doktrin inilah yang sekarang dikenal dengan doktrin “multi-culturalism”. Dan tiba-tiba saya sadar bahwa inilah yang dulu diperjoangkan oleh Baperki, yang dulu saya tentang.
Maka, sejak permulaan akhir tahun 1980an, saya mulai berbicara tentang konsep nasionalisme yang terbuka, konsep multi-kulturalisme. Dalam wawancara-wawancara terhadap pers tentang masalah Cina saya katakan orang-orang Cina harus bangga terhadap budaya Cina-nya, dan budaya itu hendaknya diperkenalkan di Indonesia untuk menambah semaraknya kebudayaan Indonesia modern. Saya katakan orang-orang Cina hendaknya tidak merasa malu untuk menyatakan ke-Cina-annya, sambil tetap menunjukkan dalam tingkah lakunya bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Saya menyadari, mengingkari diri sebagai orang Cina membuat orang-orang ini merasa rendah diri karena ada unsur Cina di dalam darahnya.[6] Tanpa sadar saya sudah berubah menjadi “anggota” Baperki, lebih dari 20 tahun kemudian setelah lembaga ini dimatikan.
Perubahan ini didukung juga oleh pertemuan saya dengan Siauw Tiong Gie dan Siauw Tiong Djin, yang juga terjadi pada tahun 1980an. Ketika pertama kali bertemu dengan Gie, saya agak waswas, karena saya masih punya gambaran yang negatip terhadap pamannya, Siauw Giok Tjhan. Saya masih bersikap sangat hati-hati.
Tapi ketika menemuinya di Koln, Jerman Barat, Gie tampil sebagai anak muda yang lincah dan cerdas. Saya tinggal di kamar kos-nya dan makan di Restoran Indonesia yang dikelola oleh keluarganya. Saya sangat terkesan dengan penampilan anak muda ini. Kami juga sempat membicarakan masalah Baperki, dan apa yang terjadi pada tokoh-tokohnya di Malang, Jawa Timur, dari mana Gie berasal. Pada waktu itu terkilas pertanyaan dalam benak saya: “Bagaimana mungkin Siauw Giok Tjhan yang secara galak berusaha mengganyang kami pada permulaan tahun 1960an, punya keturunan yang baik seperti Gie?” Tapi Gie memang bukan keturunan langsung dari Pak Siauw, jadi mungkin itu sebabnya.
Tapi, ini kemudian berubah ketika saya bertemu dengan Siauw Tiong Djin, putra langsung dari Siauw Giok Tjhan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1988, ketika saya diundang menjadi Peneliti Tamu di Universitas Monash, Melbourne, Australia.
Dia menilpon saya. Terus terang pada waktu itu, saya masih agak risih menemui putra bekas “musuh politik” saya. Tapi, setelah bertemu dengan Gie, kerisihan itu tidak cukup kuat untuk membuat saya menolak untuk membuat janji bagi sebuah pertemuan.
Kisah selanjutnya kiranya jelas. Seperti juga Gie, saya mendapatkan Djin merupakan orang yang baik hati, ramah dan sangat penolong. Saya segera menyukainya dan kami jadi bersahabat.
Tapi tampaknya trauma lama belum juga hilang. Saya masih berpikir bahwa mungkin anaknya baik, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, Siauw Giok Tjhan (atau lebih tepat lagi Baperki) sangat kasar dalam menyerang lawan-lawan politiknya. Jadi, meskipun anaknya baik, bapaknya bisa saja tidak.
Kesan negatip ini pada akhirnya luluh ketika pada tahun 1988 saya mengadakan sebuah konperensi besar, dengan bantuan Universitas Monash, tentang masalah demokrasi di Indonesia.[7] Salah satu pembicara yang diundang adalah Pak Yap Thiam Hien.
Ketika itu, Djin menilpon saya bahwa dia ingin supaya Pak Yap tinggal di rumahnya. Saya terkejut mendengarkan permintaan tersebut. Sepengetahuan saya, Siauw Giok Tjhan dan Yap Thiam Hien saling bermusuhan. Saya banyak mendengar kritik-kritik Pak Yap terhadap Pak Siauw. Terhadap permintaan Djin ini, saya katakan nanti saya akan bicarakan dulu dengan Pak Yap.
Ketika Pak Yap datang ke Melbourne, dengan hati-hati saya tanyakan apakah Pak Yap keberatan tinggal dirumah putranya Siauw Giok Tjhan? Jawabannya mengejutkan saya. Tidak samasekali! Bahkan dia merasa senang. Lalu saya tanyakan, bukankah Pak Yap bermusuhan dengan ayahnya? Dia katakan, secara politis memang mereka berseberangan, tapi dia menghormati Pak Siauw sebagai seorang idealis yang teguh pada prinsipnya. Dia juga seorang jujur yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Dia merasa senang kalau bisa tinggal bersama Siauw Tiong Djin. Pertahanan saya yang terakhir untuk mencurigai Siauw Giok Tjhan runtuh setelah percakapan ini. Saya tilpon Djin dan menceritakan apa yang dikatakan Pak Yap. Djin menyatakan bahwa ayahnya juga, meskipun berbeda pandangan politiknya, sangat menghormati Pak Yap yang juga idealis dan prinsipil ini.
Sejak itu, bagi saya tak ada masalah dengan kelakuan politik Siauw Giok Tjhan di masa lalu. Saya sadar bahwa kekasaran yang dilakukan oleh Baperki dalam mengganyang lawan-lawan politiknya ketika itu merupakan tuntutan politik pada saat tersebut. Apalagi kalau kita ingat, yang dilakukan pemerintah Orde Baru, pemerintah yang ikut saya sokong berdirinya, bertindak lebih kejam terhadap lawan-lawan politiknya. Dan apalagi pula, pada saat itu, saya sendiri sudah menyadari bahwa Doktrin Integrasi dan Multi-Kulturalisme yang diperjoangkan Baperki lebih benar ketimbang Doktrin yang diperjoangkan oleh lawannya, yakni Doktrin Asimilasi.
***
Saya tidak mengenal Siauw Giok Tjhan dalam dua arti. Pertama, saya tidak mengenalnya secara pribadi. Saya belum pernah bertemu dengan dia. Kedua, saya luput mengenalnya sebagai seorang idealis yang memperjoangkan apa yang dianggapnya benar.
Yang pertama tidak bisa saya ubah, karena yang bersangkutan sudah tiada. Yang kedua, melalui sebuah proses waktu yang lama dan panjang, berhasil saya ubah.
Karena itu sekarang dapat saya katakan, meskipun saya tidak mengenal Siauw Giok Tjhan secara pribadi, saya mengenal apa yang diperjoangkannya.
Dia, saya kira, pantas dikagumi.
———————————————————-
[1] Istilah Cina ini sebenarnya dimaksudkan dipakai untuk orang-orang Cina yang bukan warganegara Indonesia. Orang Cina yang sudah jadi warganegara Indonesia dipanggil orang Indonesia. Tapi dalam praktek, orang-orang Cina yang sudah warganegarapun dipanggil sebagai orang Cina. Kemudian, setelah istilah ini dipakai selama lebih dari 30 tahun, kita jadi terbiasa. Konotasi penghinaan sudah hilang, kecuali bagi generasi tuanya. Saya sendiri berpikir lebih baik kita adopsi saja kedua istilah itu, Cina dan Tionghoa, supaya kita tidak tersinggung lagi kalau ada orang yang menyebut kita Cina. Bukankah istilah Cina sudah jadi lazim digunakan di Indonesia sekarang tanpa bermaksud menyinggung? Inilah alasannya mengapa saya memakai istilah Cina sampai sekarang.
[2] Hal yang sebaliknya juga terjadi. Orang-orang Cina dianggap oleh orang-orang pribumi sebagai jorok, mata duitan, kelakuannya kasar dan tidak sopan (misalnya bersendawa sehabis makan) dan hal2 lain yang negatip sifatnya. Ketika saya kecil, saya ingat teman2 saya orang pribumi suka mengejek saya dengan mengatakan: “Cina loleng, makan tahi sekaleng.”
[3] Manikebu atau Manifes Kebudayaan dicetuskan oleh para seniman liberal pada tahun 1963. Kelompok militer, dalam usaha menghimpun kekuatan untuk menghadapi Bung Karno dan kelompok kiri lainnya, juga merangkul yang bergabung dalam
kelompok Manikebu ini.
[4] Untuk orang-orang yang hidup di jaman itu, tentunya slogan-slogan politik seperti ini masih akan diingat dengan jelas. Slogan-slogan politik ini diteriakkan dan dituliskan setiap hari dalam rapat-rapat politik dan media massa.
[5] Waktu itu, saya dan Hok Gie berdiskusi dengan teman kami, sarjana Amerika ahli Indonesia, Prof. Ben Anderson. Dia mentertawakan maksud kami untuk mengganti nama. Setelah kami jelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab sosial dan politik kami, dia tampaknya bisa memahami.
[6] Saya mengalami sendiri hal ini. Saya pernah, ketika remaja dulu, saya membenci diri saya karena saya lahir sebagai etnis Cina. Pada waktu itu, saya sampai menghindari berpacaran dengan gadis2 keturunan Cina, dengan tujuan supaya keturunan saya nanti bisa mengurangi “dosa asal” ini. Saya bisa bayangkan tentunya ada banyak juga pemuda2 Cina yang punya perasaan rendah diri seperti saya, karena hidup di bawah pemerintah Suharto yang menjalankan propaganda bahwa menjadi Cina di Indonesia merupakan sesuatu yang buruk.
[7] Hasil konperensi ini sekarang sudah dijadikan buku yang saya sunting sendiri, dengan judul: State and Civil Society in Indonesia, diterbitkan oleh Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Australia. Buku ini dicetak pertama pada tahun 1990, cetakan ketiga pada tahun 1994.


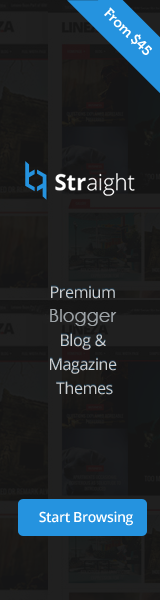




![[Catatan Siauw Tiong Djin] Arief Budiman, Sang Pejuang dan Akademisi](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeOeQdT7a_aCAFjkwF1szQcc1gfpPaonkuAJlpf3hpjzsOqwTlsquaLUYyoSKEYx3FLAldrIj3t99ued-VpX_oycRItkVCVTLjIVrWypLmI94X-p_xb6om3nkmn1R3ft3KFgznaW6i-o0D/s72-c/20200425_093644.jpg)



Tidak ada komentar
Posting Komentar